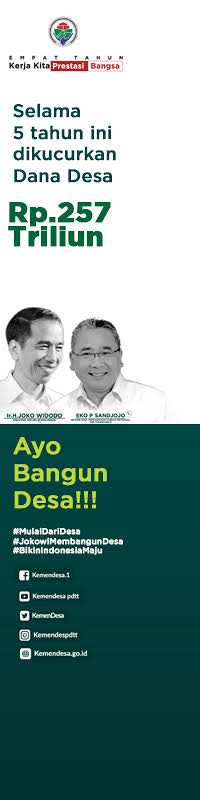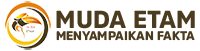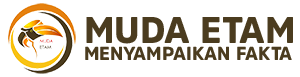OPINI Sinar Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat
Di ruang-ruang kerja modern, layar komputer, laptop, dan ponsel pintar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Hampir semua sektor—dari perbankan, pendidikan, hingga layanan publik—mengandalkan perangkat digital sebagai alat utama. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada risiko kesehatan yang sering diabaikan: kelelahan mata atau digital eye strain. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pekerja dan pelajar yang mengeluhkan mata perih, kering, pandangan kabur, hingga sakit kepala akibat menatap layar terlalu lama. Sayangnya, fenomena ini masih jarang ditempatkan sebagai bagian dari isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Menurut American Optometric Association, lebih dari 70 persen pekerja kantoran mengalami gejala computer vision syndrome (CVS). Di Indonesia, fenomena ini semakin terasa sejak pandemi Covid-19, ketika pembelajaran daring dan sistem kerja jarak jauh membuat waktu tatap layar meningkat drastis. Bagi sebagian orang, gangguan ini hanya dianggap keluhan ringan. Padahal, jika dibiarkan, kelelahan mata bisa berkembang menjadi gangguan serius, seperti peningkatan miopi, mata kering kronis, bahkan risiko penyakit degeneratif mata di kemudian hari.
Kesehatan mata adalah salah satu aspek fundamental dalam produktivitas kerja. Seorang sopir logistik dengan mata buram berisiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas. Operator mesin yang matanya cepat lelah bisa salah membaca indikator, memicu kerusakan alat bahkan korban jiwa. Sementara itu, pekerja kantoran dengan penglihatan menurun akan kesulitan berkonsentrasi, menurunkan kualitas kerja, dan akhirnya berdampak pada perusahaan.
Jika K3 dipahami sebagai upaya melindungi pekerja dari risiko kesehatan dan keselamatan akibat pekerjaan, maka jelas bahwa kelelahan mata di era digital adalah bagian dari isu K3 modern. Sayangnya, regulasi dan implementasi K3 di Indonesia masih cenderung fokus pada risiko fisik—jatuh dari ketinggian, terjepit mesin, atau paparan bahan kimia—sementara risiko visual hampir tidak mendapat perhatian.
Dasar hukum K3 di Indonesia juga mendukung hal ini. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa keselamatan kerja meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan akibat pekerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan K3, sementara PP No. 50 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Bahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 164, mewajibkan tempat kerja menyelenggarakan upaya kesehatan kerja. Artinya, isu kelelahan mata akibat layar digital seharusnya termasuk perlindungan K3 yang wajib dijalankan perusahaan.
Ada beberapa faktor yang membuat kelelahan mata kian marak. Pertama, durasi tatap layar yang terlalu panjang. Banyak pekerja menghabiskan 8–10 jam di depan komputer, lalu masih menatap ponsel untuk hiburan atau komunikasi pribadi. Kedua, kondisi kerja yang tidak ergonomis. Ruangan dengan pencahayaan buruk, layar dengan tingkat kecerahan tidak seimbang, atau posisi duduk yang salah memperparah ketegangan mata. Ketiga, kurangnya kesadaran pekerja dan perusahaan tentang pentingnya istirahat visual. Istirahat dianggap membuang waktu, padahal justru meningkatkan kualitas kerja.
Kultur kerja digital di Indonesia sering menormalisasi penggunaan gawai sepanjang waktu. Di beberapa perusahaan rintisan, pekerja bahkan dituntut selalu “siaga” melalui laptop atau ponsel, membuat mata hampir tak pernah benar-benar beristirahat. Akibatnya, gangguan penglihatan kini muncul di usia yang lebih muda. Penelitian terbaru menunjukkan peningkatan signifikan kasus miopi pada remaja dan dewasa muda di kota-kota besar, yang salah satunya dipicu oleh paparan layar berlebihan.
Kelelahan mata bukan sekadar keluhan pribadi. Jika dibiarkan, ia bisa menurunkan produktivitas nasional dan meningkatkan beban kesehatan publik. Bayangkan jutaan pekerja yang produktivitasnya menurun karena pandangan kabur, atau biaya kesehatan yang meningkat karena semakin banyak orang membutuhkan kacamata, obat tetes mata, hingga operasi.
Selain itu, risiko kecelakaan kerja akibat gangguan penglihatan tidak bisa disepelekan. Pekerja transportasi, pilot, pengemudi ojek daring, atau pekerja pabrik yang bergantung pada ketajaman penglihatan bisa menanggung risiko fatal jika kesehatan matanya terganggu. Dengan kata lain, kelelahan mata adalah “silent hazard” dalam dunia kerja modern.
Di sinilah persoalan utama: K3 kita masih terlalu “buta” terhadap isu kesehatan mata. Banyak perusahaan sudah memiliki program ergonomi tubuh—kursi yang nyaman, meja dengan tinggi tertentu—tetapi jarang yang memperhatikan ergonomi visual. Pemeriksaan mata rutin bagi pekerja hampir tidak pernah dilakukan, kecuali di sektor khusus seperti penerbangan.
Menurut saya, sudah waktunya paradigma K3 diperluas. K3 tidak boleh hanya melindungi pekerja dari benda yang jatuh atau mesin yang berputar, tetapi juga dari risiko kesehatan akibat budaya kerja digital. Perlindungan mata harus menjadi prioritas, karena tanpa penglihatan yang sehat, pekerja tidak mungkin bisa optimal.
Pertama, pemerintah perlu memasukkan kesehatan mata dalam regulasi K3. Misalnya dengan mendorong perusahaan menyediakan pemeriksaan mata rutin, mengatur waktu kerja berbasis layar, serta memastikanstandar pencahayaan ruang kerja.
Kedua, perusahaan perlu membangun kesadaran tentang pentingnya istirahat visual. Konsep aturan 20-20-20—setiap 20 menit menatap layar, pandang objek sejauh 20 kaki selama 20 detik—bisa disosialisasikan sebagai kebiasaan kerja sehat. Selain itu, fasilitas kerja seperti layar anti-silau, pencahayaan alami, dan penataan ruang ergonomis harus menjadi investasi, bukan dianggap biaya.
Ketiga, pekerja juga harus lebih proaktif menjaga kesehatan mata. Menggunakan kacamata dengan lensa pelindung radiasi biru, menjaga jarak pandang ideal, serta membatasi penggunaan gawai untuk hiburan setelah bekerja adalah langkah sederhana namun berdampak besar.
Kelelahan mata di era digital adalah bom waktu yang pelan tapi pasti merongrong produktivitas bangsa. Jika K3 terus mengabaikan aspek ini, kita akan menghadapi generasi pekerja dengan kualitas penglihatan yang menurun sebelum waktunya.
Sudah saatnya Indonesia menegaskan bahwa K3 bukan hanya soal fisik yang kasat mata, melainkan juga kesehatan organ vital yang bekerja dalam senyap. Mata yang sehat adalah fondasi produktivitas. Dan melindungi mata berarti melindungi masa depan kerjakita.